
SURABAYA (Lentera) -Akademisi sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof Dr Didik J Rachbini, M Ec mengkritik praktik yang dilakukan sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN). Ia melihat semakin banyak PTN yang mengalami disorientasi atau salah arah.
"Saya mencermati sekarang terjadi disorientasi kampus-kampus yang harus mengemban amanah mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya dalam diskusi bertajuk "Evaluasi & Outlook Pendidikan Tinggi & Riset Menuju Kampus Global" yang digelar Universitas Paramadina via Zoom, Selasa (16/12/2025).
Didik menyoroti semakin tingginya kuota mahasiswa baru di PTN setiap tahunnya. Beberapa PTN bahkan dapat menerima lebih dari 20 ribu mahasiswa baru dalam satu tahun.
Kecaman Prof. Didik terhadap perguruan tinggi negeri yang membuka kran penerimaan mahasiswa terlalu lebar layak dibaca sebagai peringatan serius.
Bukan sekadar kritik personal, melainkan alarm tentang arah pendidikan tinggi kita. Sebab bukan hanya soal jumlah mahasiswa, melainkan soal kejujuran kampus dalam mengenali batas kemampuan dirinya.
Di negeri ini, kampus sering diminta tetap idealis, tapi dibiayai dengan prinsip “cukup tahu”. Anggaran negara mengalir tersendat, sementara tuntutan mutu tetap deras. Maka PTN pun belajar bertahan hidup dengan cara paling sopan: tidak berjualan terang-terangan, cukup menambah daya tampung. Tidak menyebutnya obral, melainkan perluasan akses. Bahasa tetap akademik, meski logika pasar diam-diam memimpin rapat.
Masalah mulai terasa ketika kran dibuka lebar, sementara pipa lama tak pernah diganti. Ruang kuliah sesak, dosen mengajar lintas kelas dengan stamina yang diuji. Mahasiswa pun belajar tentang kompetisi bahkan sebelum sempat memahami etika akademik.
Kampus pun perlahan berubah menjadi ruang antre: antre kelas, antre bimbingan, antre masa depan. Inilah demokratisasi pendidikan versi barisan panjang.
Ironisnya, situasi ini sering dirayakan sebagai capaian. Grafik penerimaan naik, laporan terlihat sehat, dan institusi merasa berhasil “melayani masyarakat”. Soal mutu? Itu urusan jangka panjang.
Sedihnya, biasanya sepanjang masa jabatan berikutnya.
Kampus tetap disebut pusat keunggulan, meski keunggulan kini lebih sering diukur dari kuantitas, bukan kedalaman berpikir.
Tidak Seimbang
Dampak kebijakan ini tidak berhenti di dalam pagar kampus negeri. Perguruan tinggi swasta ikut merasakan getarannya. Ketika PTN membuka kran penerimaan tanpa rem yang jelas, PTS menghadapi limpahan kompetisi yang tidak seimbang. Yang satu disubsidi negara, yang lain bertahan sepenuhnya dari uang kuliah.
Ini bukan persaingan mutu. Lebih pas disebut perlombaan bertahan hidup. Di balik kran PTN yang mengalir deras, ada PTS yang diam-diam mengering. Bukan karena kalah kualitas, tapi karena berbeda perlakuan kebijakan.
Di sinilah penting membedakan antara memperluas akses dan mengobral bangku kuliah. Akses adalah soal keadilan sosial; obral adalah soal ketergesaan institusional. Kampus yang bermartabat tahu kapan membuka pintu, dan lebih penting lagi, berani menutupnya. Sayangnya, keberanian berkata “cukup” sering kalah oleh kebutuhan menutup laporan keuangan.
Namun, tidak adil jika seluruh kesalahan ditimpakan ke kampus. Negara meminta PTN mandiri, lalu terkejut ketika PTN berperilaku mandiri. Kita menginginkan kampus steril dari logika pasar, tapi lupa bahwa logika itu masuk melalui pintu anggaran yang setengah terbuka. Sulit menuntut idealisme penuh dari lembaga yang diminta hidup dari setengah keyakinan negara.
Cermin Bersama
Kritik Prof. Didik semestinya menjadi cermin bersama. Kampus perlu bercermin agar tidak silau oleh angka penerimaan. Negara perlu bercermin agar tidak terus percaya bahwa ilmu pengetahuan bisa tumbuh subur di tanah yang dipupuk seadanya. Sementara masyarakat—ini bagian yang jarang disentuh—perlu bercermin bahwa pendidikan tinggi bukan sekadar tangga sosial, melainkan proses pendewasaan berpikir.
Jika kran mahasiswa terus dibuka tanpa menghitung daya tampung akademik dan nurani, maka mahasiswa perlahan bergeser dari subjek pendidikan menjadi objek pembiayaan. Ilmu pengetahuan tetap diajarkan, tapi prioritasnya berubah: dari mencerdaskan ke mencukupkan. Dari membangun karakter ke menjaga arus kas.
Menyiram tanaman dengan ember bocor memang tampak meyakinkan dari kejauhan. Airnya banyak, tanah terlihat basah, tetapi akar tetap kering. Ketika panen gagal, kita kembali bertanya: mengapa kampus tidak lagi melahirkan keunggulan?
Mungkin karena sejak lama, kita terlalu sibuk menghitung debit air, dan lupa merawat akarnya.
Kran penerimaan mahasiswa dibuka lebar bukan karena air melimpah, melainkan karena tagihan terus datang. Maka ketika Prof. Didik Rachbini mengingatkan bahaya praktik ini, yang seharusnya tersentak bukan hanya kampus, melainkan sistem yang membuat kampus belajar bertahan hidup dengan cara seperti itu.
Pernyataan Didik tentang PTN yang gemar menambah mahasiswa seharusnya tidak dibaca sebagai kemarahan moral, melainkan sebagai pertanyaan mendasar: sejak kapan pendidikan tinggi mengukur keberhasilannya dari banyaknya kursi terisi, bukan dari mutu pikiran yang dibentuk!?!
Penulis: Zainal Arifin Emka, Wartawan Tua, Pengajar Stikosa-AWS|Editor: Arifin BH


-jpg.jpg)


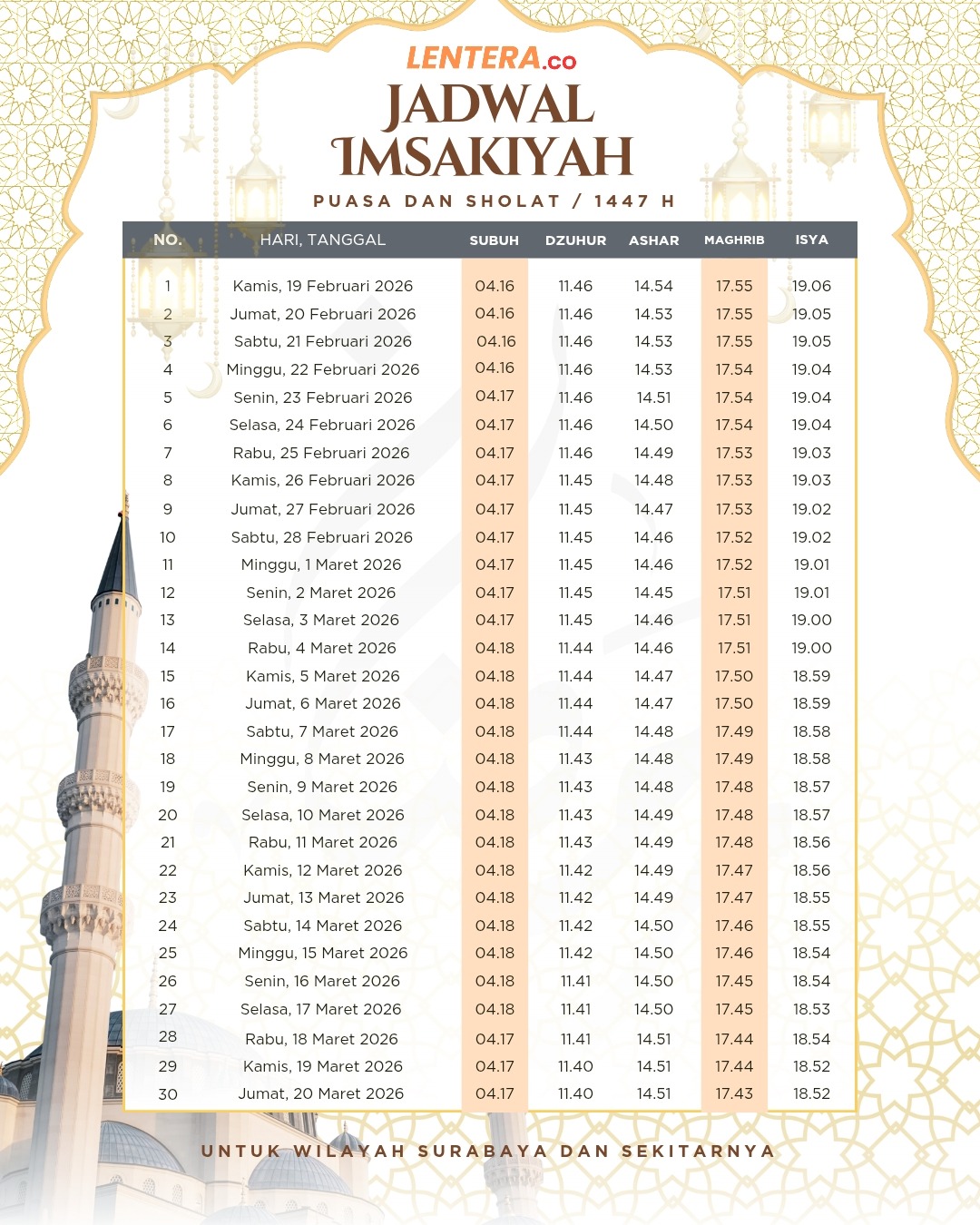
.jpg)
