
OPINI (Lentera) -Pemimpin suatu negeri diibaratkan Sang Naga, yang lahir secara alami dari suatu perjuangan panjang penuh pengorbanan, dan tanpa pamrih (misal Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, serta para pejuang bangsa yang melahirkan ideologi dan konstitusi lainnya).
Kelahiran alami pemimpin terjadi dengan syarat tanpa campur tangan bisnis, karena bisnis mengandung konten transaksional.
Dalam negara demokrasi di era kapitalisme dan liberalisme, kelahiran sosok pemimpin bisa jadi tidak alami (buatan), karena merupakan hasil interaksi kompleks antara ‘bakat alami individu’ dan ‘pengaruh sistemik’, termasuk peran kelompok elit atau mekanisme “branding” dibelakangnya, karena masyarakat harus dicekoki opini yang membangun obsesi walau tidak sesuai kenyataan (distorsi realitas) melalui media dan narasi gencar di era digitalisasi.
Rakyat yang tingkat intelektualitasnya sebagian besar menengah ke bawah, dengan kecerdasan kritis yang relatif rendah, terjebak dalam persepsi yang keliru akibat branding dan pembentukan opini-persepsi publik.
Pemimpin "Lahir Alami" vs ‘Buatan’
Pemimpin alami terlahir karena kualitas intrinsik dan dukungan rakyat. Beberapa pemimpin muncul karena kemampuan alami seperti kharisma, kecerdasan emosional, atau visi yang selaras dengan aspirasi publik. Nelson Mandela, misalnya, yang menjadi simbol perjuangan anti-apartheid tanpa dukungan elit.
Pemimpin seperti Bernie Sanders (AS) atau Jacinda Ardern (Selandia Baru) meraih pengaruh melalui keterlibatan langsung dengan masyarakat, media sosial, atau isu progresif, tanpa bergantung sepenuhnya pada struktur partai tradisional.
Pengaruh kelompok elit (oligarkis) sering menggunakan branding politik melalui partai-partai politik sebagai "gerbang" kepemimpinan, untuk melahirkan sosok pemimpin ‘buatan atau boneka’. Kandidat perlu dukungan finansial, jaringan, dan legitimasi dari elit partai.
Elit media atau konsultan politik dapat membentuk citra publik melalui kampanye terstruktur. Kasus Jair Bolsonaro (Brasil) atau Emmanuel Macron (Prancis) menunjukkan bagaimana media dan narasi yang diarahkan oleh elit berperan besar.
Di era global, keterlibatan korporasi atau kelompok kepentingan (melalui donasi kampanye) sering menentukan siapa yang bisa bersaing dalam pemilu, seperti di banyak demokrasi kapitalis.
Dalam situasi yang demikian demokrasi bak arena pertarungan antara’legitimasi vs manipulasi’.
Demokrasi idealnya memungkinkan pemimpin berbakat muncul melalui meritokrasi, tetapi praktiknya, akses ke sumber daya (uang, media, jaringan) sering kali dimonopoli oleh para elit.
Sistem pemilu baik proporsional dan distrik, transparansi pendanaan kampanye, dan kebebasan pers, menentukan sejauh mana elit bisa mendominasi proses.
Media sosial menggeser kekuatan dari elit tradisional ke masyarakat, tetapi juga memungkinkan "manufactured populism" yang disokong algoritma dan buzzer politik.
Pemimpin Buatan Rentan Akhir Yang Kacau
Mengapa pemimpin "produk branding elite" menyebabkan rentan kacau di akhir masa jabatannya, bahkan setelah suksesi kepemimpinan?
Pemimpin buatan pada awal jabatannya akan memainkan performance yang apik dan elegan sesuai harapan rakyat pemilih. Tetapi ekosistem rahim kelahirannya menuntut kompensasi ekonomi finansial sebagai ganti ongkos biaya branding dan pemenangan.
Sosok pemimpin buatan pun akan memberi ‘ruang’ korupsi secara tersembunyi melalui berbagai kebijakan yang dikemas secara patriotik nasionalistis dan kerakyatan.
Tetapi korupsi (baik uang maupun penyalahgunaan kewenangan) selalu melahirkan jerat dan menghilangkan batas “kecukupan”. Tidak ada kata “cukup” dari uang dan kekuasaan. Semua diterabas bahkan melampaui ‘outer limit’ etika sosial, politik, ekonomi dan budaya.
Kolusi, nepotisme dan dinasti menjadi bagian integral dari suatu sistem kekuasaan yang koruptif. Judi online pun ditunggangi menjadi kendaraan favorit penggalangan dana, juga penataan saham investasi berbagai bisnis corporate (dimana oknum penguasa merekayasa saham investasi dengan dalih ‘golden share’) sebagai ajang pencarian uang untuk mempertahankan kelangsungan kekuasaan. Pada gilirannya uang yang dihimpun adalah sebagai money politics utamanya untuk melindungi berbagai skandal penyelewengan yang diupayakan keras ditutupi.
Dengan latar belakang yang demikian, akhir kekuasaan sosok pemimpin buatan niscaya memasuki fase krisis dan kritis untuk mengakhiri kekuasaan dan menjamin ‘keselamatan’ pasca suksesi.
Negeri demokrasi yang berpenduduk besar, tidak mungkin bisa selalu di rangkul untuk persuasi, karena biayanya menjadi besar tidak terbatas; disamping benih-benih kekecewaaan dan kemarahan akibat beberapa clue skandal korupsi, kolusi dan nepotisme selama masa jabatan si pemimpin buatan tidak mudah dikendalikan.
Sang Naga Menjadi Sang Rubah
Pemimpin buatan di akhir masa jabatan selalu masuk dalam kepanikan, sehingga banyak blunder dalam kebijakan, narasi dan tindakan. Kombinasi antara ambisi berkuasa yang membara, dan upaya membabibuta untuk melindungi dan menutupi berbagai potensi skandal yang tersembunyi.
Sistem jaringan institusional yang dibentuk untuk melindungi pemimpin buatan dan menjamin loyalitas, hanya bersifat jangka pendek, karena perubahan jaman, perubahan striktur kepentingan, usia yang mengurangi kegesitan berinteraksi dan bernarasi dan juga kenekatan karena ambisi.
Nepotisme berupa pembentukan semacam dinasti kekuasaan dalam negara demokrasi sangat tabu dan mendapat respon negatif dari masyarakat luas.
Pemimpin buatan sering terperangkap dalam ambisi tanpa kompetensi. Sejarah mencatat pemimpin yang dipaksakan naik melalui mesin partai korup seperti kasus Jacob Zuma di Afrika Selatan terjerat skandal besar karena kurangnya kapasitas mengelola kekuasaan. Ambisi untuk mempertahankan kekuasaan atau memperkaya diri bisa membuat mereka mengabaikan kebijakan rasional, seperti korupsi massal atau nepotisme.
Pemimpin buatan yang tidak pernah merasakan pahit getirnya perjuangan dan pengorbanan sering easy going dalam membangun narasi overpromise. Branding elite sering dibangun melalui narasi populisme atau janji muluk maka ketika pemimpin gagal memenuhi janji, krisis legitimasi muncul. Sejarah mencatat Jair Bolsonaro(Brasil) gagal menangani COVID-19 dan deforestasi Amazon, meski awalnya di-branding sebagai "penyelamat konservatif".
Kerentanan pemimpin buatan juga disebabkan ketergantungan pada elite pendukung. Mereka yang lahir dari kendali elite tidak sepenuhnya independen. Mereka harus memenuhi tuntutan kelompok pendukungnya (misal: oligarki, militer, atau korporasi). Konflik kepentingan berkembang kompleks dan ini bisa memicu kerentanan akan ‘keselamatan’ pemimpin buatan.
Branding politik para elite oligarkis bukanlah "perisai abadi". Ada batasan yang membuatnya rapuh ketika kepemimpinan mulai kacau; atau membuat pemimpin buatan dan elit dibelakangnya terancam serius ketika krisis legitimasi di mata publik meluas. Masyarakat modern semakin kritis terhadap narasi media yang dikendalikan elite. Skandal korupsi atau kinerja buruk mudah terungkap melalui platform digital. Liz Truss (Inggris) jatuh dalam 45 hari karena kebijakan ekonominya memicu krisis pasar; elite konservatif tidak bisa menyelamatkannya meski awalnya mendukung penuh.
Fragmentasi para elite pendukung makin luas karena elite bukan kelompok monolitik. Ketika pemimpin merugikan sebagian dari mereka (misal: kebijakan yang mengancam bisnis oligarki), dukungan bisa retak.
Sejarah mencatat Nayib Bukele (El Salvador) kehilangan dukungan internasional karena otoritarianisme, meski awalnya dianggap "inovatif".
Tarian Akhir Sang Rubah
Semakin mengakhiri masa jabatannya sosok pemimpin buatan makin melemah kekuasaannya. Gelar sebagai Sang Naga bergeser menjadi Sang Rubah karena harus cerdik menghindari perburuan dan cerdik untuk bersembuyi. Para elit menjauh karena tidak mau bisnis mereka terseret dalam skandal besar
"The Crucible", suatu skenario drama karya Arthur Miller ditulis tahun 1953
berkisah tentang "Perburuan Penyihir Salem" di masa kolonial Amerika. Kekuasaan hakim dan pemimpin agama yang tiranis runtuh ketika masyarakat sadar bahwa tuduhan hanyalah rekayasa untuk mengontrol politik.
Karya sastra ini sebagai metafora mengkritik terhadap McCarthyisme (anti-komunis di AS tahun 1950-an) dengan pesan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan dan ketakutan akan hancur ketika kebenaran terungkap.
Kekuasaan pemerintahan yang tidak lahir alami dari rakyat, akan melahirkan Sang Naga palsu, sosok pemimpin boneka yang terbelit dalam kompleksitas kepentingan oligarkis. Konyolnya pemimpin boneka sebagai OBPP (orang baru peran penguasa) selalu oportunis dan meledak ambisinya.
Dari seorang lemah yang ‘tiba-tiba’ jadi penguasa besar akan mengalami dislokasi sosial secara serius; menjadi sosiopat (tidak tahu malu), lalu terlena dalam ambisi yang berbahaya, membabi buta mencapai kekuasaan langgeng dan membangun dinasti legenda turun temurun. Sungguh merepotkan kelompok elit oligarkis pendukungnya. Pilihannya hanya berkisar opsi ditinggal, atau dikorbankan. Itulah akhir tarian Sang Rubah.
Apa yang dikisahkan, memberi pelajaran tentang demokrasi yang sehat, yaitu demokrasi yang membutuhkan keseimbangan antara meritokrasi (pemimpin kompeten) dan kontrol sistemik (transparansi, akuntabilitas). Tanpa ini, pemimpin "produk branding" akan terus menjadi sumber krisis, sementara elite hanya akan sibuk mencari pengganti yang lebih patuh.
Haruskah Indonesia terjebak terus menerus dalam siklus Sang Naga vs Sang Rubah? Nampaknya akan terus terjebak jika masyarakat terkena virus oportunis, dimana kompensasi jabatan dan bansos politik dianggap berkah dari Tuhan yang terus dikejar, tidak peduli siapa dan apa reputasi calon pemimpin (*)
Penulis: Hadi Prasetya, pengamat sosial - ekonomi|Editor: Arifin BH


-jpg.jpg)


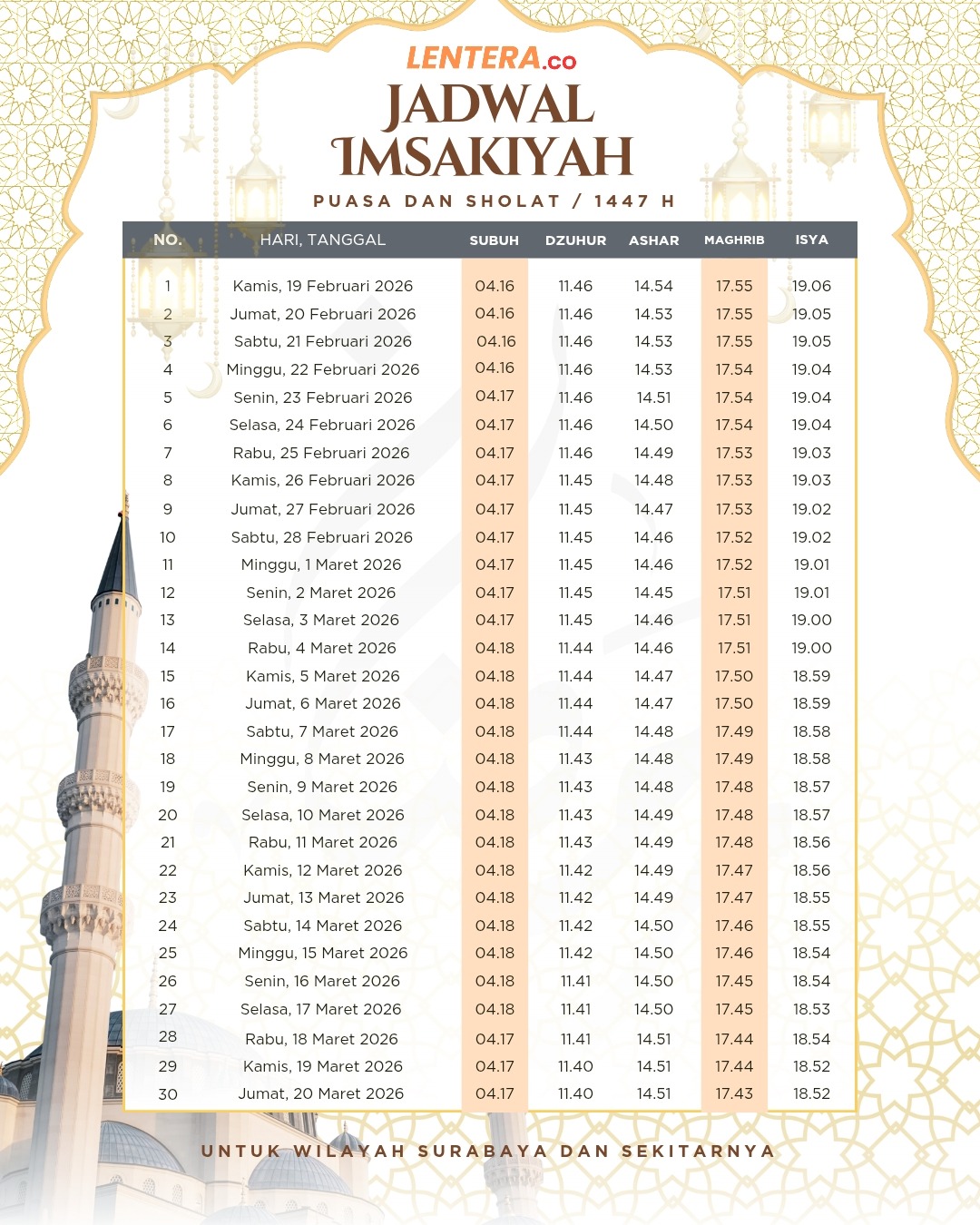
.jpg)
