
Pukul 10:00 WIB, suasana Kampus Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo, Surabaya mulai ramai. Sekitar 20-an mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi telah duduk di ruang kelas lantai 3. Para mahasiswa tengah menunggu hadirnya seorang dosen yang konon paling galak di kampus itu.
Berselang 2 menit kemudian, sang dosen memasuki ruangan. Sosoknya tinggi tegak. Berjalan pelan ke depan kelas menghadap para mahasiswa. Rambutnya keriting telah memutih seluruhnya. Dia tidak tersenyum. Menyapa, lalu mengabsen dengan memanggil satu persatu nama mahasiswa di kelas itu.
Ketika prosesi absensi, seseorang mengetuk pintu kemudian dan memasuki ruang kelas. Seorang mahasiswa datang terlambat. Sang dosen menunjukkan wajah kesal. Prosesi absensi langsung berganti menjadi prosesi interogasi terhadap mahasiswa yang terlambat, yang berlangsung sekitar 5 menit.
Akhir interogasi, si mahasiswa bisa duduk di ruang kelas dengan peringatan keras bagi mahasiswa di kelas itu.
"Jangan ada yang terlambat lagi, apapun alasannya!" tegasnya.
Prosesi absensi pun dilanjutkan kembali.
Prof Sam Abede Pareno, memang dosen yang tegas. ('Galak', red). Tetapi bukan itu yang membuat saya selalu mengenangnya hingga di waktu ia berpulang, hari ini, Sabtu (30/4/2022).
Saat itu, sekitar 6 tahun lalu, di kelas yang sama, di tengah diskusi tentang kebebasan pers di Indonesia, ia mendadak bertanya kepada saya. "Anda agama apa?"
Saya pikir, pertanyaan itu tidak berhubungan dengan topik diskusi di kelas hari itu. Saya tidak menjawab pertanyaan itu.
Prof Sam mengulang lagi, "Anda agama apa?"
Saya tersenyum dan mengumpat dalam hati. Pertanyaan apapun akan saya jawab semampu saya, tapi sejujurnya pertanyaan ini benar benar tidak mampu saya jawab saat itu.
Tak mendengar jawaban dari saya, ia bertanya lagi pertanyaan yang sama untuk ketiga kalinya. "Anda agama apa?" tanyanya.
Sebagian mahasiswa di kelas itu, melontarkan aneka jawaban, mulai Katolik, Islam, atheis, bahkan ada yang menebak: Nusantara. Saya masih juga tidak mampu mengucapkan sebuah jawaban.
Dalam hati, saya berharap, bisa menghilang dari hadapannya saat itu juga. Namun pandangannya tetap menuntut jawaban. Akhirnya saya menjawab, "Belum tahu Pak."
Dia tersenyum. "Ya," ucapnya singkat.
Senyuman itu tidak berhasil menenangkan batin dan pikiran saya yang mendadak kacau saat itu.
Saya tidak mengerti, mengapa ia tidak bertanya kepada mahasiswa yang lain? Mengapa hanya kepada saya? Di tengah diskusi Kebebasan Pers. Apakah di dahi saya tertulis "tidak beragama" atau "krisis spiritualitas" atau apa lagi?
Seluruh kelas membahas puluhan jurnalis yang menjadi korban kekerasan, penganiayaan hingga penghilangan nyawa karena pemberitaan yang mengancam kelompok atau seseorang, dan hingga kini kasus kekerasan terhadap para jurnalis masih abu-abu, mengapa ia menanyakan, apa agama saya?
Detik berikutnya, Prof Sam kembali melanjutkan diskusi dengan topik Peran Dewan Pers, sementara di kepalaku pertanyaan itu masih terasa menggedor- gedor batinku.
Enam bulan kemudian, saya mulai menjalankan ritual ibadah sebuah agama, hingga saat ini. Tetapi bukan ini, yang menjadi catatan penting bagi saya.
Yang menggores dalam benak saya, tentang bagaimana sorang Prof Sam Abede Pareno telah mengetuk pemikiran, memancing pola pikir dari carut marutnya kegelisahan sebuah generasi.
Dunia wacana ilmu komunikasi, filsafat ilmu, jurnalistik, sastra, bahasa, bahkan ilmu kehidupan yang mengejawantah dalam ucapan, tulisan, perilaku serta kebijakan dan keputusannya, diberikan kepada para mahasiswa tanpa tendensi, selain perkembangan dan kemajuan ilmu itu sendiri bagi generasi berikutnya.
Prof Sam telah menjalankan peran seorang dosen, seorang pendidik penuh dedikasi, dengan semua tulisan, kata-kata, teguran, bahkan juga senyuman untuk generasi bangsa ini.
Selamat jalan Prof. Sam Abede Pareno! Tukisan ini sebagian kecil memoar. Teman Anda di alam Akhirat!
Penulis: Endang Pergiwati, wartawan Lenteratoday


-jpg.jpg)



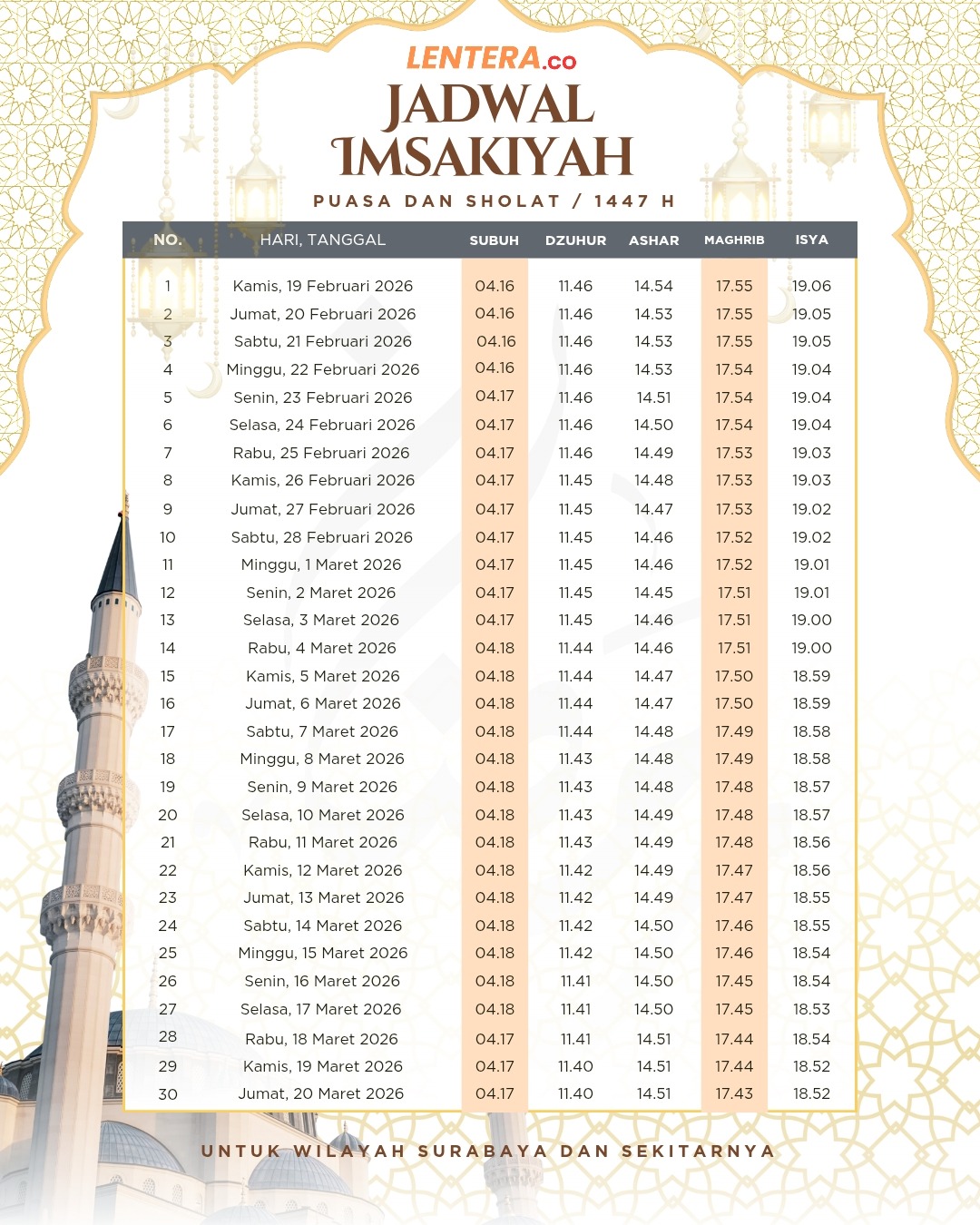
.jpg)
