
SURABAYA (Lentera) - Sejak manusia menjadi makhluk yang berpikir dan mulai mempelajari alam semesta, kita telah menempuh perjalanan panjang untuk memahami satu kenyataan penting, yaitu bahwa manusia bukanlah pusat dari segala sesuatu di jagat raya.
Kesadaran ini membuka pintu bagi pemahaman baru mengenai sifat alam semesta. Dari pemikiran ini muncul berbagai model kosmologi, seperti latar gelombang mikro kosmik (CMB) dan metrik FLRW (Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker), yang menggambarkan alam semesta yang terus mengembang, dan temuan ini kemudian dikonfirmasi melalui pengamatan astronomi.
Prinsip yang menjadi dasar pemikiran ini dikenal dengan nama Prinsip Copernicus, yaitu ide bahwa manusia tidak menempati posisi yang istimewa di alam semesta. Fisikawan Albert Stebbins dari Fermilab pernah menjelaskannya pada tahun 2008.
“Bukan hanya kita tidak hidup di bagian istimewa alam semesta, tapi memang tidak ada bagian istimewa sama sekali. Segalanya kurang lebih sama di mana pun,” papar Stebbins seperti dikutip Phys.org.
Artinya, ketika menatap langit malam, kita sebenarnya melihat masa lalu alam semesta, yang bisa dianggap sama pentingnya dengan masa lalu kita di Bumi. Prinsip Antropik menekankan bahwa makhluk sadar hanya bisa ada di alam semesta yang mendukung kehidupan, sehingga kita berada di tempat yang “ramah” bagi kehidupan. Beberapa ilmuwan bahkan memperluas pemikiran ini ke waktu, melalui teori “Carter Catastrophe” atau Doomsday Argument, yang menyatakan kita mungkin hidup di titik acak dalam sejarah umat manusia, bukan di awal maupun akhir.
Astrofisikawan Australia Brandon Carter pertama kali mengajukan ide ini, dan kemudian dikembangkan oleh J. Richard Gott pada 1993. Gott menjelaskan bahwa, jika kita menganggap posisi kita di sepanjang waktu benar-benar acak, kita bisa memperkirakan berapa lama lagi manusia akan bertahan sebelum punah.
Dengan menggunakan pendekatan probabilistik, Gott memperkirakan bahwa waktu yang telah berlalu (sejak manusia ada) bisa menjadi indikator kasar seberapa lama lagi kita bisa bertahan.
“Ada peluang 95% bahwa masa depan kita berada di antara 1/39 hingga 39 kali dari waktu yang telah berlalu,” papar Gott, mengutip IFLSceince.
Untuk membuktikan idenya, Gott tidak langsung memprediksi kiamat, ia mengujinya pada hal yang lebih sederhana: Tembok Berlin.
Ketika mengunjungi Tembok Berlin pada 1969, ia memperkirakan bahwa dinding tersebut akan bertahan antara 1/39 hingga 39 kali lebih lama dari umur yang sudah dijalaninya. Dua puluh tahun kemudian, Tembok Berlin benar-benar runtuh, tepat di kisaran prediksi probabilistiknya.
Gott kemudian menerapkan metodenya pada Stonehenge yang berusia sekitar 3.900 tahun dan hasilnya tetap masuk akal. Dengan model sederhana dan data kelahiran hingga 1993, ia memperkirakan total manusia yang akan lahir antara 1,8 miliar hingga 2,7 triliun, dengan keyakinan 95%. Jika kelahiran tetap sekitar 145 juta per tahun, manusia kemungkinan bertahan kurang dari 19.000 tahun lagi.
“Namun kalau kita ingin memperpanjang harapan hidup hingga 7,8 juta tahun ke depan, maka laju kelahiran rata-rata harus turun hingga 400 kali lipat,” kata Gott.
Tentu saja, prediksi ini tidak pasti, karena kemajuan medis atau peningkatan harapan hidup bisa memperpanjangnya, sementara perang nuklir atau perubahan iklim ekstrem bisa mempersingkat umur manusia.
Meski terdengar seperti ramalan kiamat, para ilmuwan menekankan bahwa “Doomsday Argument” bukanlah nubuat, melainkan alat berpikir statistik untuk memahami posisi kita dalam rentang waktu tertentu. Balik lagi, soal kiamat kita serahkan semuanya pada pemilik alam semesta, Tuhan.
Co-Editor: Nei-Dya/berbagai sumber


-jpg.jpg)


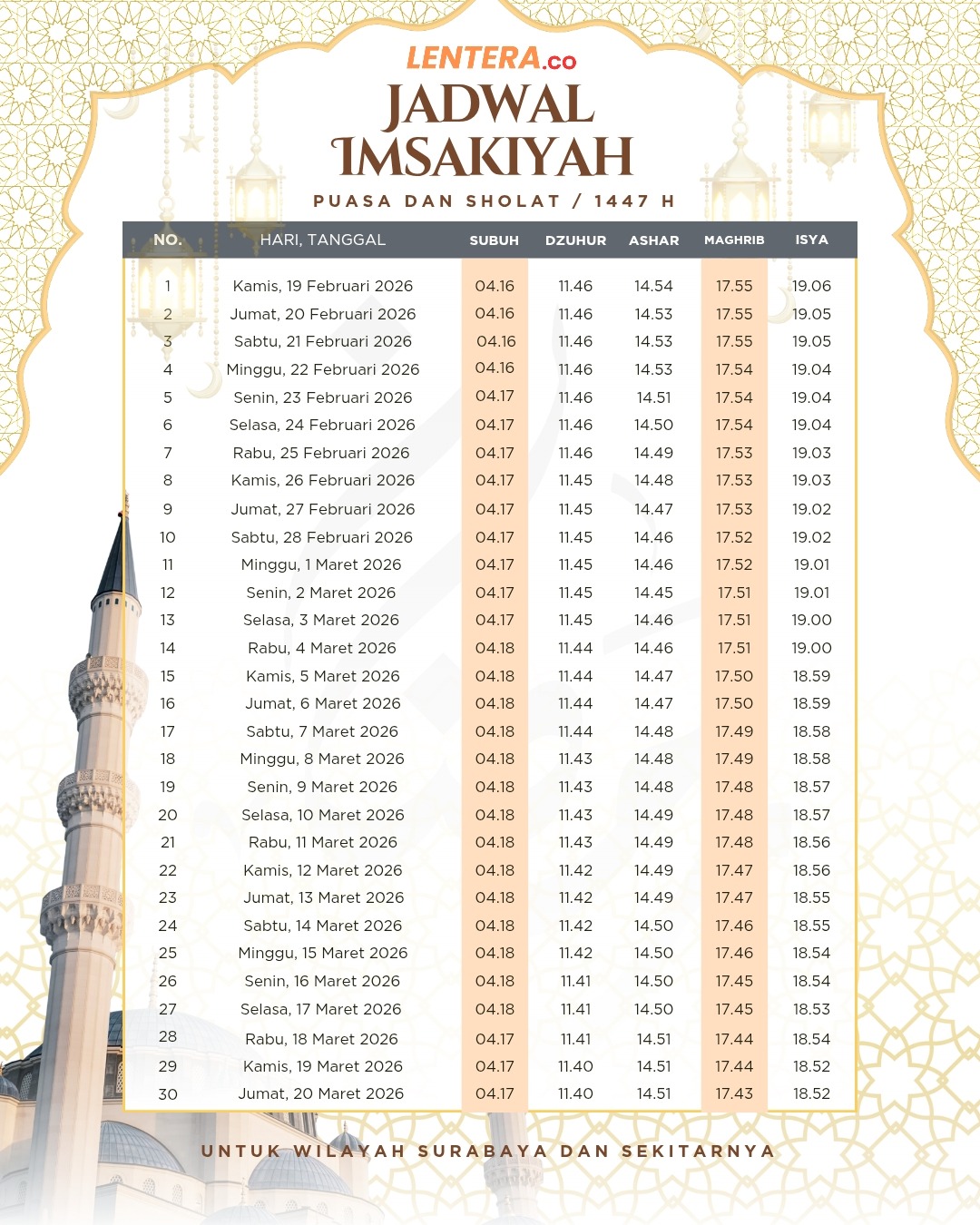
.jpg)
